Persoalan konversi dan kerusakan hutan terjadi karena buruknya tata kelola hutan (bad-forest governance). Berbagai kebijakan diterbitkan untuk menjawab persoalan kehutanan, tetapi laju deforestasi tetap menjadi permasalahan besar di Indonesia, walaupun upaya perbaikan fungsi hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan telah dilakukan. Bahkan sejak tahun 1980an kebijakan kehutanan telah diarahkan untuk menyelesaikan masalah lahan kritis dan memperbaiki pasokan kayu industri. Persoalan-persoalan kerusakan hutan lebih mengerucut pada pada tiadanya kejelasan institusi pengelola di tingkat tapak. Akibatnya terjadi konflik para pihak yang berkepentingan. Untuk mengatasi kekosongan pengelola di tingkat tapak, diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Salah satu tugas pokok KPH adalah mengembalikan dan memperbaiki fungsi hutan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Rehabilitasi hutan menjadi kerengka kerja yang utama di kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat (KPHL RB). Wilayah kelola KPHL RB secara umum berada pada wilayah kerja Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Dodokan Moyosari. BPDAS Dodokan Moyosari telah menetapkan bahwa setiap tahun, wilayah kerja KPHL RB minimal terdapat 4.000 ha luasan lahan kritis sehingga harus dilaksanakan program rehabilitasi hutan serta pengayaannya. KPHL RB mempunyai tanggung-jawab ini menjadi cukup besar, mengingat wilayah kerja KPHL RB mempunyai sejarah tenurial yang cukup panjang, khususnya di daerah Sesaot dan Rempek. Konflik tenurial telah terjadi sejak rejim pengelolaan Hindia Belanda dan berlanjut pada rejim Orde Baru. Perlawanan masyarakat utamanya didorong oleh putusan Dinas Kehutanan yang mengambil-alih wilayah kelola masyarakat dan lebih memberikan kepercayaan kepada korporasi swasta Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dibandingkan kepada masyarakat. Perlawanan mencapai puncaknya disaat reformasi, yaitu warga menduduki dan membakar kantor korporasi swasta. Selain ruang kelola warga yang direbut oleh negara, pemerintah, telah terjadi dampak negatif terhadap ekosistem, seperti berkurangnya persediaan air, dan sebagainya yang diindikasikan oleh warga akibat keberadaan korporasi tersebut. Pasca perlawanan tersebut, warga menolak setiap program-program pemerintah, baik dari Dinas Pertanian dan Perkebunan, ataupun dari Kehutanan. Penolakan tersebut didasari oleh rasa/sikap traumatik yang dialami masyarakat. Atas dasar itulah, Dinas Kehutanan membentuk tim untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait persoalan tenurial yang ada. Tim inilah yang mempelopori terjadinya rekonstruksi pemahaman kehutanan dilingkungan Dinas Kehutanan, Rimbawan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Upaya perubahan diskursus di lingkungan rimbawan diwujudkan pada institusi(onal) KPHL RB. Pada akhirnya, kegiatan dan aktivitas program KPHL RB bisa diterima oleh masyarakat bahkan terjadi kolaborasi bekerja bersama antara KPHL RB dan masyarakat/tani hutan. Kerangka kerja rehabilitasi hutan menjadi ‘bangunan’ kolaborasi/kemitraan dalam pengelolaan hutan antara masyarakat dan KPHL RB, meskipun beberapa kebijakan RHL tidak memungkinkan terjadinya skema kerjasama secara luas, seperti penentuan jenis tanaman dan lain sebagainya. Hal demikian bisa terus berjalan karena adanya sebuah penafsiran ulang aparatus-birokrasi, street-level bureaucracy (SLB) terhadap peraturan-perundangan, rehabilitasi hutan dan lahan. Tafsir SLB berkaitan pada kebebasan aparatus-birokrasi dalam menentukan, dan mengambil keputusan (kebijakan) yang memungkinkan dengan kondisi dan fenomena sosial-lingkungan yang ada. Kebebasan dalam menentukan dan mengambil keputusan, lazimnya disebut dengan diskresi. Terdapat beberapa praktik diskresi yang diterapkan oleh SLB di KPHL RB. Pertama, penentuan lokasi rehabilitasi hutan. Pada umumnya dan menurut petunjuk penetapan lokasi rehabilitasi didapatkan melalui pendekatan spasial citra, yaitu ditemukannya luasan lahan kritis yang kemudian ditetapkan/diputuskan sebagai lokasi/objek rehabilitasi. Diskresi yang diterapkan adalah, mencari kepastian subjek/masyarakat/petani yang akan melaksanakan program. Dari petani (rumah tangga) yang akan mengelola didapatkanlah luasan rehabilitasi. Kedua, berkaitan pada jenis tanaman. Jenis tanaman yang dipilih diserahkan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan tetap mempertahankan fungsi tata air. Ketiga, rekrutmen tenaga kerja lapangan. Inovasi yang diterapkan adalah penyesuaian terhadap tenaga kerja lapangan (kontrak) yang disetujui melalui alokasi APBN dan wilayah garapan/kelola. Praktik diskresi seperti ini sangat memungkinkan dalam mengatasi persoalan alokasi anggaran. Keempat, perangkat penunjang. Minimnya alokasi anggaran berimplikasi pada sarana dan perangkat penunjang program rehabilitasi hutan. Jenis tanaman yang dipilih oleh masyarakat dominan tanaman buah, bukanlah tanaman kayu. Hal ini berimplikasi pada satuan harga yang lebih tinggi. Alokasi anggaran yang tersedia tidak mencukupi dalam pengadaan bibit tanaman buah. SLB KPHL RB menerapkan diskresi melalui pembangunan perangkat penunjang secara semi-swadaya bersama masyarakat. Berbagai praktik diskresi yang telah diterapkan oleh KPHL RB dapat diterima oleh masyarakat karena adanya konstruksi diskursus pengelolaan hutan pada jajaran birokrasi KPHL RB. Selain itu, sejarah tenurial menjadikan setiap SLB KPHL RB menjadi lebih dekat dengan masyarakat, dan landasan kerja pada SLB adalah pelayanan publik/masyarakat dan mewujudkan kelestarian alam-hutan/lingkungan.
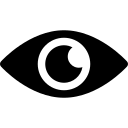
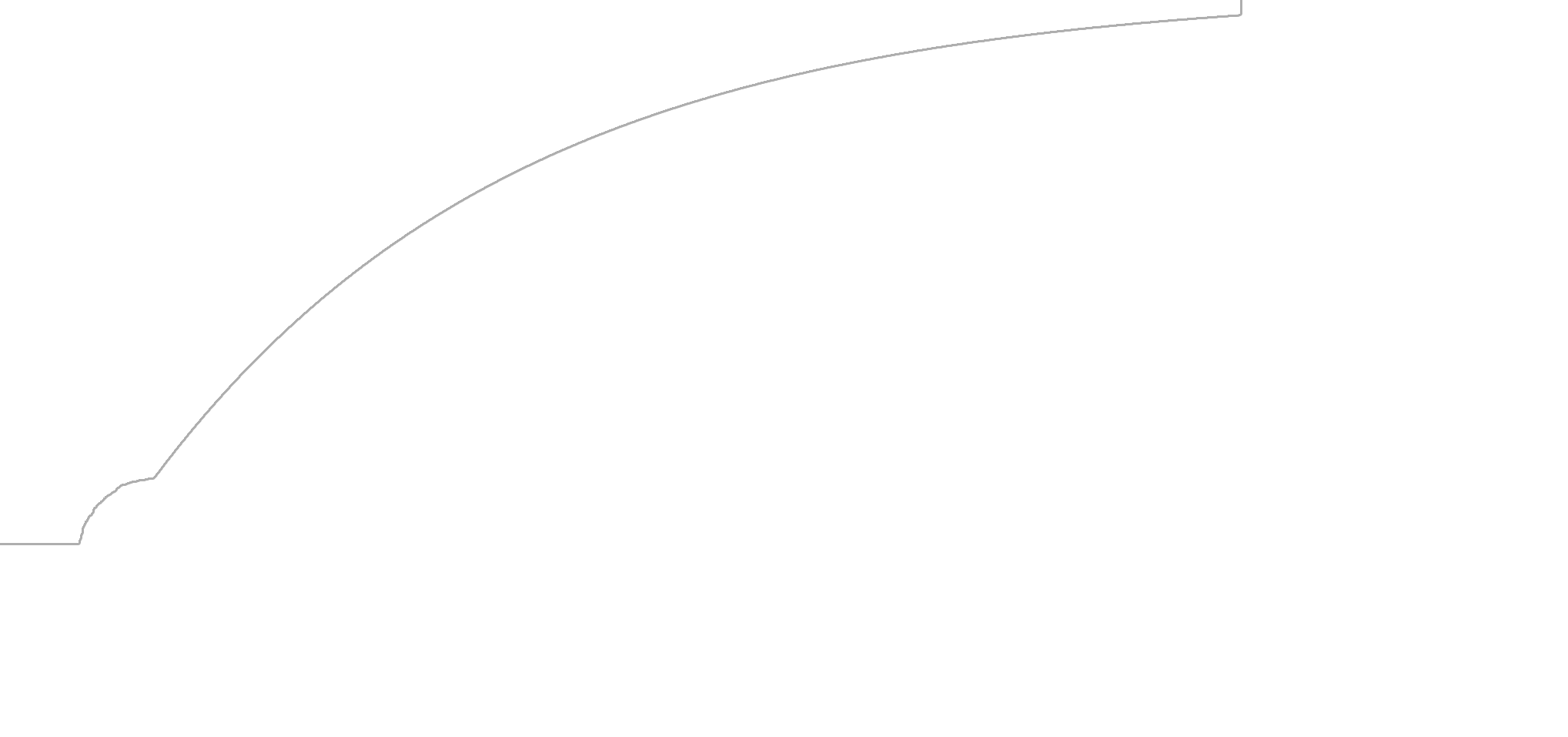






 Ada pertanyaan mengenai pengalaman ini ? Diskusikan pada kolom komentar ini
Ada pertanyaan mengenai pengalaman ini ? Diskusikan pada kolom komentar ini